Komersialisasi Pendidikan Tinggi
|
| PENDIDIKAN sejatinya menjadi alat pembebasan. Pendidikan sebagaimana dikattakan filsuf Belanda, Dahrenduff, adalah alat perjuangan kelas. Lewat pendidikanlah manusia mampu mengangkat kelas sosialnya. Pendidikan yang baik menjadikan manusia berpikir dan bertindak bijaksana dan adil. Karena itu, seluruh anak bangsa harus merasakan pendidikan secara merata. |
| Dunia pendidikan Indonesia terus berdialektika menuju
bentuk terbaiknya. Dalam konteks pendidikan tinggi Indonesia hari ini
misalnya, kampus di seluruh Indonesia didesain sedemikian rupa agar
berorientasi industri. Apa makna industri di sini? Melalui UU No 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, jawaban atas pertanyaan tersebut
akan didapat. Tentu sangat ironis, dunia pendidikan tinggi saat ini
telah sampai pada fase komersialisasi. Sebelumnya, kelahiran UU tentang Pendidikan Tinggi (PT) pada 2012 menuai demonstrasi. Resistensi dari berbagai elemen mahasiswa terhadap UU ini adalah bentuk nyata menolak komersialisasi pendidikan tinggi. Skema komersialisasi pendidikan tinggi tersebut tak lain misi terorganisir dari neoliberalisme yang hendak menihilkan peran negara di semua lini kehidupan masyarakat. Liberalisasi di bidang pendidikan ini salah satu contohnya. Bagian UU tentang PT yang dipandang melegalkan komersialisasi pendidikan adalah pasal 64 dan 65, mengatur otonomi perguruan tinggi. Pasal ini memberikan pilihan penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi bagi PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU) atau membentuk badan hukum. Otonomi yang diberikan meliputi bidang akademik maupun non akademik termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dalam rangka menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Di antara kewenangan PTN yang berbadan hukum adalah hak mengelola dana secara mandiri, mendirikan badan usaha, dan mengembangkan dana abadi. Diktum inilah yang oleh sebagian kalangan 'dicurigai' sebagai bentuk pelarian tanggung jawab pemerintah dari pemenuhan semua beban biaya pendidikan. Pasal inilah landasan awal PT menjadikan kampus layaknya perusahaan, walaupun di pasal sebelumnya yakni pasal 60 maupun 63 prinsip pengelolaan kampus adalah bersifat nirlaba, jadi tidak mengutamakan untung. Namun, tetap saja praktiknya di lapangan banyak sekali kasus yang menunjukkan uang kuliah tak sebanding dengan kelas si mahasiswa dan tak kunjung membaiknya fasilitas kampus. Lebih spesifik, dalam pembiayaan aktivitas perkuliahan, uang kuliah tunggal (UKT) dianggap sebagai jalan untuk memberi keadilan bagi mahasiswa. Namun polemik terkait UKT sampai hari ini masih menyisakan ketimpangan yang nyata di mahasiswa, prinsip keadilan masih di atas kertas, dalam praktiknya masih jauh dari ekspektasi. UKT adalah sistem pembayaran kuliah dengan penghapusan uang pangkal bagi mahasiswa angkatan 2013 hingga sekarang, tetapi mahasiswa diharuskan membayar sejumlah uang yang besarnya sama tiap semesternya hingga mereka lulus. Dalam UKT ini besarnya biaya per-semester bergantung dari besar kecilnya pendapatan orang tua mahasiswa, untuk selanjutnya dikelompokan dalam golongan tertentu. Pengelompokan ini ditujukan untuk pemberian subsidi silang antara mahasiswa dari golongan tinggi ke rendah. Yang senantiasa menimbulkan polemik di masyarakat adalah perumusan parameter untuk mengklasifikasikan kemampuan orangtua dalam membayar UKT. Mampukah merepresentasikan sebuah keadilan? karena mekanisme penggolongannya yang acap kali menuai kontroversi. Paradoks UKT inilah yang membuat ketimpangan yang nyata di mahasiswa, tak jarang mereka yang orang tuanya hanya berjualan di pinggir jalan yang pendapatannya tak tentu dibebankan uang kuliah yang sama dengan mahasiswa yang orang tuanya pegawai negeri sipil yang notabene memiliki pendapatan tetap. Dimana UKT yang berkeadilan itu ? Kampus yang telah bervisi industri tak peduli akan hal ini karena kampus hari ini melihat mahasiswa sebagai 'income', jadi bukan manusia yang harus dididik dengan nilai-nilai humanisme. Masih Milik Si Kaya Sungguh ironis bagi bangsa Indonesia yang sebentar lagi memasuki usia 71 tahun, sampai detik ini belum menaruh fokus pada pendidikan yang sejatinya alat perjuangan kelas masyarakat serta peradaban Indonesia. Dalam konteks kekinian, pendidikan tinggi semakin menunjukkan keberpihakannya pada kelas masyarakat yang berduit. Mari sejenak renungkan kebijakan Kemenristeksikti terkait kuota penerimaan mahasiswa baru PTN. Dikutip dari website resmi SNMPTN 2016, Ketua Panitia SBMPTN 2016 Rochmat Wahab menuturkan, tahun ini Kemenristikdikti mengubah persentase kuota penerimaan mahasiswa baru. Jika di tahun lalu jalur SNMPTN menampung 50 persen, SBMPTN 40 persen dan jalur mandiri 10 persen, tahun 2016 ini SNMPTN menampung 40 persen, SBMPTN dan jalur mandiri masing-masing 30 persen. Ada yang menarik dari kuota tersebut yakni bertambahnya kuota jalur masuk mandiri. Sebelumnya kuota mandiri hanya 10 persen, artinya tahun ini mahasiswa yang hendak mendapatkan kursi reguler akan bertarung keras dengan mereka yang hendak mendapatkan kursi mandiri. Sejatinya kompetisi ini tak adil karena mahasiswa jalur mandiri lebih diutamakan, padahal mereka berasal dari kelas menengah ke atas masyarakat Indonesia dan mampu membayar berapa pun jumlah uang kuliahnya. Dalam Permenristek Dikti Nomor 2 Tahun 2015, SBMPTN dan Seleksi Mandiri PTN tergabung dalam satu kategori yaitu seleksi mandiri. Bedanya, SBMPTN dikelola secara terpusat untuk semua PTN, sedangkan Seleksi Mandiri PTN dikelola masing-masing PTN yang menyelenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat kampus yang telah diberikan hak otonom dalam mengelola sendiri rumahnya, maka sangat logis jika kampus lebih mengutamakan kepentingan internalnya, yakni keuntungan. Peserta yang membludak dan kursi yang sangat sedikit pun dipolitisasi agar memberi keuntungan besar. Kuota 30 persen jalur mandiri tersebut terlalu berlebihan dan sangat memarjinalkan masyarakat miskin. Oleh karena itu, sangat utopia kampus hari ini berbicara produksi manusia-manusia Indonesia yang adil sejak dalam pikiran. Benarlah, orang miskin dilarang sekolah, pendidikan Indonesia hanya milik kelas masyarakat tertentu. Kampus seyogianya mampu menjunjukkan kesetaraan sebagai institusi pendidikan tinggi, kampus seharusnya mampu memancarkan ide-ide persamaan dan keadilan bagi masyarakat. Kampus tak etis jika pongah terhadap salah satu kelas masyarakat. Namun kini pendidikan tinggi di Indonesia tampaknya sedang terserang virus komersialisasi tingkat akut. Sebagaimana diatur di dalam pasa 28C ayat 1 UUD 1945: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian ditegaskan di dalam pasal 31 ayat 1: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sesuai konstitusi pendidikan harus diberikan secara egaliter, namun dalam praktiknya rakyat dibedakan antara si kaya dan si miskin. Sudah saatnya kuota untuk beasiswa rakyat miskin diberikan dalam jumlah besar. Mereka harus diberikan kesempatan besar untuk mengenyam pendidikan tinggi. Pendidikan adalah benteng terakhir perjuangan kelas masyarakat, maka tidak sepantasnya ranah pendidikan tinggi ikut dikomersilkan. Negara wajib hadir dalam memastikan rakyatnya mendapatkan pendidikan secara merata. (Oleh: Rafyq Panjaitan) Penulis mahasiswa FISIP Universitas Sumatera Utara |
Organisasi ini bernama GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA disingkat GMNI. Organisasi ini didirikan pada tanggal 23 Maret 1954. GMNI berazaskan Marhaenisme, yaitu Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Friday, June 17, 2016
Komersialisasi Pendidikan Tinggi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ORGANISASI CIPAYUNG

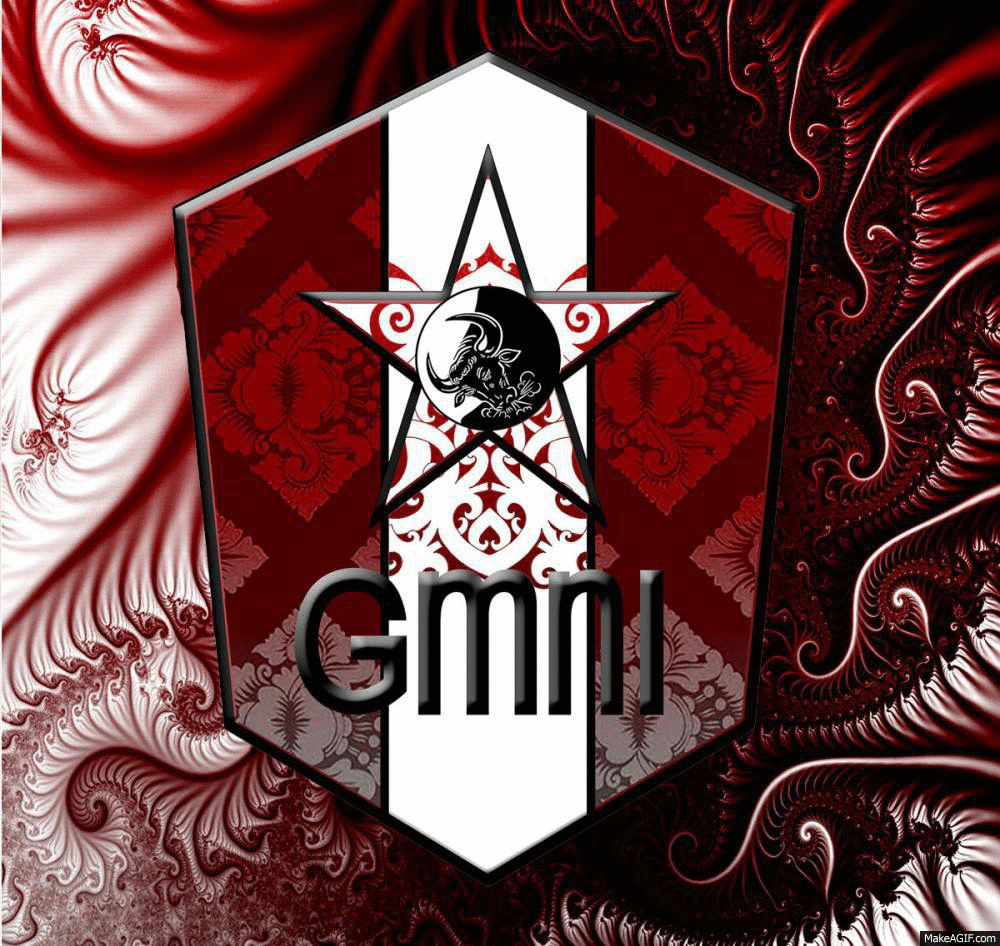
No comments:
Post a Comment